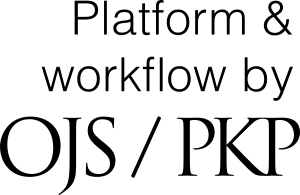Samar

Yuwanda Efrianti
Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam
UIN Imam Bonjol Padang
Tak salah jika Abdullah Khusairi seorang dosen literasi media pernah menulis, “Ketika kebohongan sudah menyebar ke seluruh dunia, kebenaran bahkan belum sempat mengenakan celananya.” Hari ini, mungkin celana itu pun sudah tak ditemukan lagi.
Kalimat bisa berdarah bila jari-jari terlalu ringan. Di zaman ketika pesan lebih cepat sampai daripada pikir, banyak kepala dilubangi bukan oleh peluru, melainkan oleh kalimat yang keliru dibaca, dipahami setengah, dan disebar utuh-utuh.
Teknologi tak pernah salah. Tapi manusia sering terlalu percaya pada kecepatan, seolah cepat itu setara dengan cerdas. Maka lahirlah pemikiran ketika kebenaran ditunda karena fakta kalah viral, dan keadilan dikerangkeng dalam kolom komentar. Yang bersuara lantang dianggap pahlawan, meski tak satu pun ucapannya berdiri di atas data.
Ada yang rusak di dalam tubuh sosial hari ini. Sebab kecepatan menyampaikan pesan tak lagi diimbangi kecepatan berpikir. Semua serba kilat. Hanya perlu satu sentuhan untuk menyebar, tapi butuh waktu seumur hidup untuk menebus dampaknya.
Jean Baudrillard pernah memperingatkan bahwa ketika simbol menjadi lebih nyata dari kenyataan, manusia tidak lagi hidup di dunia melainkan di refleksi bias informasi. Yang palsu tampak otentik. Yang nyata tampak aneh. Dan itulah yang sedang terjadi.
Sejalam dengan itu laporan Digital 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 85% warga digital Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber utama kabar sehari-hari. Dari angka itu, lebih dari separuh tak sempat menakar ulang apakah yang mereka telan layak disebar atau justru racun yang dikemas dengan gaya ramah.
Dalam banjir data yang mengalir 24 jam sehari, yang tercecer bukan sekadar logika. Nalar, nurani, dan iman pun ikut terseret. Manusia tak lagi berpikir sebelum mengirim. Ia cukup merasa.
Dalam bukunya Teologi Informasi, Abdullah Khusairi menulis bahwa setiap informasi yang datang akan melewati alam pikir dan di sanalah teologi seseorang bekerja tanpa sadar. Pengetahuan masa lalu, pengalaman spiritual, nalar sosial, bahkan ego, semuanya berpadu. Inilah yang menentukan apakah kabar itu dicerna atau ditelan bulat-bulat.
Agama, yang seharusnya jadi rem, kini ikut diseret jadi umpan klik. Nama Tuhan dibungkus kutipan, dikirim dalam format meme, lalu dijadikan bahan saling hujat. Dalam data PPIM UIN Jakarta 2022, ditemukan lonjakan penyebaran paham ekstrem di kanal-kanal yang menyamar dengan simbol keagamaan. Bukan lagi berdakwah, melainkan mempolitisasi surga.
Manusia-manusia masa ini tak sekadar lapar pengetahuan. Mereka haus pengakuan. Maka berbicara menjadi kebutuhan, walau tidak semua punya isi.
Bukan hal yang baru. Tapi jadi lebih berbahaya ketika publik mengira mereka sedang berpikir padahal hanya sedang menggulir layar. Menyimak setengah. Memutuskan sepenuhnya.
Marshall McLuhan menyebut bahwa manusia membentuk alat, lalu alat membentuk manusia. Saat ini, alat bernama ponsel telah membentuk generasi yang mengira opini adalah kebenaran, jumlah suka adalah validasi, dan yang paling keras berarti paling benar.
Dalam hening antara klik dan bagikan, barangkali yang hilang bukan sekadar akal sehat. Tapi kemauan untuk jeda. Untuk menyimak lebih lama. Untuk membiarkan satu kabar didiamkan sejenak sebelum jadi keputusan.
Tak ada yang lebih ironis dari masyarakat yang mengira sedang cerdas padahal hanya sedang terburu-buru. Seperti seseorang yang membaca tajuk berita lalu mengaku tahu seluruh ceritanya. Seperti pengendara yang memacu kendaraan di jalan berkabut, yakin tahu arah hanya karena pernah melewatinya sekali.
Ketika orang memilih bersuara sebelum berpikir, yang terjadi bukan percakapan melainkan kekacauan. Di ruang yang mestinya penuh pertimbangan, yang lahir justru saling serang. Bukan karena tak punya data, tapi karena malas memahaminya. Bukan karena tak mengerti, tapi karena merasa tak perlu.
Di sinilah pentingnya membangun kepekaan, bukan sekadar kemampuan. Seperti seorang nelayan tua yang tak hanya tahu cara mendayung, tapi bisa membaca perubahan arah angin dari warna langit. Seperti perempuan renta yang mengenali musim hanya dari rasa tanah. Itulah yang seharusnya ditumbuhkan kecakapan mengenali isyarat zaman sebelum terbawa derasnya.
Bukan tak boleh bicara. Tapi memilih diam dalam waktu-waktu tertentu adalah keberanian yang nyaris punah. Diam bukan kalah. Ia adalah cara tertua dalam berpikir. Seperti pohon yang tak berbicara namun menyimpan ribuan napas.
Maka ketika semua orang berlomba berbicara, jangan ragu menjadi yang menunduk, mendengar, dan memahami. Di situlah ruang baru terbuka. Ruang yang tak digerakkan oleh sinyal atau jaringan, tapi oleh rasa hormat pada kebenaran yang tak bisa diburu.
Tak semua informasi perlu disebarkan. Tak semua opini harus disuarakan. Tak semua kebisingan layak didengar.
Kini, keberanian tak lagi hanya soal siapa paling nyaring bicara. Tapi siapa yang mau mengambil waktu lebih lama untuk membaca utuh, menyaring dalam-dalam, dan diam ketika yang lain berebut bicara.
Satu klik mungkin terasa sepele. Tapi ia bisa mengubah arah berpikir ratusan kepala. Bahkan bisa menentukan apakah seseorang diselamatkan atau dijatuhkan.
Dan jika manusia tak kunjung berhenti, maka informasi akan menyamar jadi tuhan. Di mana siapa pun bisa jadi nabi. Dan kebenaran hanya soal siapa paling dulu menyebarkan.
-Teologi Informasi