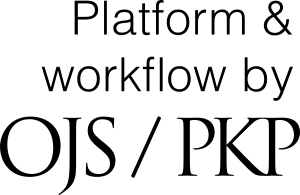Solusi Butuh Akar, Bukan Sekadar Gimmick

Yuwanda Efrianti
Peserta Sibac-Sip Australia
Ide Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka memasukkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum pendidikan, hal ini sempat terdengar seperti langkah futuristik. Canggih, keren, dan terdengar seperti solusi dari masa depan yang menembus langit harapan Indonesia. Tapi mari kita tarik napas dulu apa ini benar solusi, atau malah jebakan teknologi yang bisa berakhir jadi bencana sunyi di ruang-ruang kelas?
Gibran mengatakan AI bukan ancaman, tapi alat bantu. Ia ingin generasi muda melek teknologi sejak dini agar tak kalah di persaingan global (Kompas, 2025). Oke, niatnya mulia. Tapi, kenyataan di lapangan jauh dari imajinasi ruang belajar berteknologi tinggi. Banyak sekolah di Indonesia masih berjuang untuk punya meja cukup, guru tetap, dan sinyal internet yang tidak lenyap di tengah presentasi PowerPoint. Mau bicara AI, sementara sebagian siswa masih belajar dengan papan tulis tambalan dan kapur putih yang patah. Apakah ini bukan seperti memberi drone ke nelayan yang perahunya saja masih bocor?
Masalahnya tak berhenti di infrastruktur, isu etika digital juga makin kusut. Kasus Gibran saja di media sosial membuktikan bagaimana netizen lebih cepat menertawakan daripada memahami. Ciuman meme yang viral, komentar sarkas yang kejam, dan olok-olok tanpa batas seolah jadi tontonan harian. Penelitian tentang komentar netizen di TikTok terhadap Gibran menunjukkan betapa jauhnya kita dari literasi digital yang etis. Ujaran kebencian, serangan personal, sampai penghinaan jadi santapan harian di kolom komentar.
Ini yang sering dilupakan, teknologi boleh canggih tapi kalau manusianya tidak dibekali etika, hasilnya bisa kacau. Kebebasan berekspresi memang hak semua orang, tapi hak itu punya pagar bernama tanggung jawab. AI bukan penyihir, dia tak bisa menyulap sistem pendidikan rusak menjadi surga belajar hanya dengan satu kebijakan. Solusinya mungkin datang dari niat baik, tapi eksekusinya perlu lebih dari sekadar semangat digitalisasi. Ia butuh fondasi guru yang paham teknologi, kurikulum yang relevan, dan siswa yang siap bukan cuma secara teknis, tapi juga mental.
Maka sebelum berlari ke AI, mungkin kita harus belajar berjalan dulu dengan jujur menyelesaikan persoalan klasik pendidikan, membekali siswa dengan etika, dan mengingatkan bahwa kemajuan itu bukan soal perangkat, tapi peradaban. Jangan sampai niat jadi solusi, malah berubah jadi bencana diam-diam yang merusak dari dalam.
Wakil Presiden Indonesia memang bukan satu-satunya yang percaya pada potensi AI. Negara-negara maju sudah lebih dulu melibatkan AI dalam sistem pendidikan mereka. Tapi bedanya, mereka membangun sistem itu dengan rencana matang dan infrastruktur mapan. Di Indonesia, jika implementasi dilakukan tergesa-gesa, kita justru bisa membentuk generasi yang "kenal alat tapi tak tahu arah".
Apa gunanya AI jika digunakan oleh siswa yang lebih mahir membuat meme daripada memahami moral? Apa gunanya robotika jika diskusi-diskusi kelas masih dipenuhi hinaan, bukan gagasan? Ini bukan tentang menolak kemajuan. Ini soal menyiapkan generasi yang tak hanya pintar secara teknologi, tapi juga bijak dalam berperilaku. Etika digital bukan opsi tambahan tapi ia fondasi. Kita tak hanya butuh pengguna teknologi, tapi juga penjaga nilai.
Karena pada akhirnya, teknologi akan terus berkembang. Tapi nilai, tanggung jawab, dan batasan dalam berekspresi itulah yang menentukan apakah kita akan jadi bangsa yang unggul atau justru tenggelam dalam gelombang digital yang kita buat sendiri.
Sebab teknologi bukan tujuan akhir. Ia hanya alat. Dan jika manusia lupa bagaimana cara menjadi manusia, maka sehebat apa pun alatnya kita tetap akan tersesat.
Salam Komunikasi